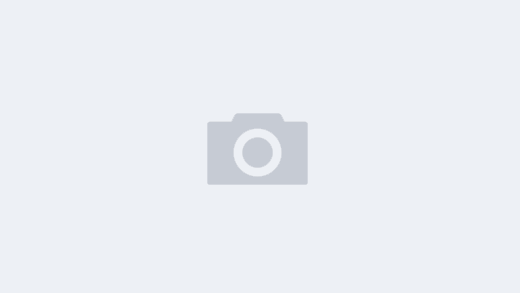Ada sesuatu yang janggal dalam narasi ekonomi Indonesia belakangan ini. Di satu sisi, kita mendengar kabar gembira: IHSG menguat, likuiditas mengalir, roda ekonomi tampak berputar. Di sisi lain, angka-angka fiskal bercerita hal yang berbeda. Defisit APBN 2025 melebar menjadi 2,92% dari proyeksi awal 2,53%, atau kenaikan sekitar 15%. Pendapatan negara turun 3,3% secara tahunan, sementara belanja justru naik 2,7%.
Saya tidak bermaksud menjadi pesimis tanpa dasar. Namun ketika melihat konfigurasi angka-angka ini, sulit untuk tidak bertanya: sedang menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, atau sekadar ilusi akuntansi yang dihias dengan indikator-indikator permukaan?
Memahami Dulu: Kas Negara Bukan Berarti Tidak Defisit
Sebelum melangkah lebih jauh, ada kekeliruan mendasar yang perlu diluruskan. Banyak orang mengira bahwa jika negara punya uang besar, berarti tidak defisit. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda.
Kas negara berbicara soal kondisi hari ini, yaitu apakah pemerintah punya uang tunai untuk beroperasi. Defisit APBN berbicara soal neraca setahun penuh, yaitu apakah total pemasukan lebih kecil dari total pengeluaran. Maka, negara bisa saja punya kas yang cukup, tetapi tetap mencatatkan defisit kalau belanja tahunan melampaui penerimaan pajak.
Lantas bagaimana dengan dana Rp200 triliun yang disalurkan Bank Indonesia ke perbankan BUMN? Di sinilah sering terjadi kerancuan. Dana itu bukan uang APBN untuk belanja, dan bukan pula untuk menutup defisit. Fungsinya adalah menambah likuiditas perbankan: supaya bank punya cukup dana untuk menyalurkan kredit ke dunia usaha. BI berperan menjaga kelancaran peredaran uang, bukan menambah pendapatan negara.
Dengan kata lain, meski dana triliunan mengalir, defisit tetap ditentukan oleh selisih penerimaan dan belanja negara. Tidak berubah.
Anatomi Defisit yang Melebar
Data Kementerian Keuangan dalam APBN KiTa menunjukkan gambaran yang cukup jelas. Pendapatan negara turun 3,3% secara tahunan, terutama karena lemahnya penerimaan pajak. Di sisi lain, belanja negara naik 2,7%, didorong oleh belanja pemerintah pusat yang meningkat 4,2%, sementara transfer ke daerah justru turun 1,7%.
Dengan bahasa yang lebih sederhana: pemasukan negara lebih rendah dari perkiraan, sementara pengeluaran lebih tinggi dari rencana. Atau dalam bahasa yang lebih kontras: setelah pergantian menteri, laju belanja tumbuh lebih cepat daripada kemampuan penerimaan.
Yang terasa ironis adalah pada saat proyeksi defisit masih 2,53%, kebijakan yang diambil justru menekankan efisiensi ke bawah. Pembangunan infrastruktur yang seharusnya menggerakkan gairah UMKM di daerah dan membuka ekonomi rakyat justru dipangkas. Sementara itu, ruang di level atas tetap longgar. Ketika asumsi fiskal memburuk, pola ini bukannya diperbaiki, melainkan malah diuji dengan belanja yang kian agresif.
Ambil contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran awal Rp71 triliun ternyata hanya cukup sampai pertengahan tahun. Zulkifli Hasan sendiri mengakui dibutuhkan tambahan Rp140 triliun untuk semester kedua, dan mulai 2026 program ini akan menelan Rp400-420 triliun per tahun. Angka Rp71 triliun saja sudah setara 90% dari total belanja perlindungan sosial Kementerian Sosial tahun 2024.
Lalu ada belanja alutsista yang mencapai lebih dari Rp170 triliun sepanjang 2025, mencakup 42 unit jet tempur Rafale senilai Rp129 triliun, dua kapal tempur dari Italia senilai Rp18,9 triliun, dan berbagai pengadaan lainnya. Kementerian Pertahanan bahkan mengajukan tambahan anggaran Rp184 triliun untuk 2026.
Kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri sebesar 8-12% juga turut menambah beban. Belum lagi penambahan 22 kementerian baru yang membuat Kabinet Merah Putih membengkak dari 34 menjadi 54 anggota, dengan konsekuensi biaya operasional, kantor baru, dan infrastruktur birokrasi yang tidak sedikit.
Defisit 2,92% kini mendekati batas maksimum yang diizinkan regulasi di level 3%. Ruang fiskal menyempit.
Likuiditas Tanpa Permintaan: Seperti Menyiram Tanah yang Tidak Mau Menyerap
Di sinilah keraguan saya terhadap efektivitas kebijakan penyaluran dana Rp200 triliun menjadi lebih konkret.
Masalah utama ekonomi Indonesia hari ini sebenarnya bukan likuiditas. Bank-bank besar sudah relatif longgar. Yang lemah justru adalah permintaan kredit yang sehat. Dunia usaha menahan diri bukan karena uangnya tidak ada, melainkan karena iklim usaha belum memberi rasa aman.
Selama kebijakan pemerintah belum konsisten melindungi produksi dalam negeri, belum tegas membangun hambatan impor, bahkan terkesan membuka lebar keran impor dari Amerika, Tiongkok, dan Eropa, serta belum memberi sinyal yang stabil ke sektor riil, tambahan likuiditas justru berisiko melahirkan kredit murah yang salah sasaran.
Ibarat menyiram tanah yang sudah jenuh air. Air baru tidak terserap ke akar, melainkan mengalir ke tempat lain.
Ujung-ujungnya, dana lebih mudah lari ke area berisiko: kredit macet, spekulasi saham, kripto, atau instrumen lain. Sementara usaha riil tetap adem ayem. Di titik ini, likuiditas bukan mendorong ekonomi, tapi memindahkan risiko ke sistem keuangan.
Saham “Bangkit dari Kubur” dan Pergeseran Uang
Beberapa minggu setelah pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya, muncul apa yang disebut sebagai “terobosan”: penyaluran dana Rp200 triliun lewat Bank Indonesia ke perbankan BUMN. Saat kebijakan itu diumumkan, saya sempat menduga ke mana arah uang akan mengalir.
Logikanya sederhana: ketika sektor riil belum benar-benar bergerak, tapi likuiditas tiba-tiba dilonggarkan dan bunga dimurahkan, dana cenderung mencari jalan yang cepat. Saham, terutama yang harganya sudah lama tidur, menjadi tempat yang masuk akal.
Dan sejak November hingga Desember 2025, perkiraan itu semakin terlihat nyata. Saham-saham yang selama ini “tidur panjang” mulai ramai diperdagangkan, harganya bergerak naik tanpa ditopang perubahan fundamental yang berarti.
Apakah keduanya berkaitan langsung? Saya tidak bisa membuktikan secara definitif. Namun polanya cukup konsisten dengan hipotesis awal: saham-saham yang harganya sudah lama tidur menjadi tempat yang masuk akal bagi likuiditas baru. Bukan karena fundamentalnya tiba-tiba membaik, melainkan karena modal kecil bisa menggerakkan harga, risikonya tampak tersembunyi di balik harga rendah, dan dana segar mudah masuk.
Kalau asumsi ini benar, maka kenaikan tersebut lebih menunjukkan pergeseran uang, bukan pemulihan bisnis.
IHSG yang naik, yang sangat dibanggakan oleh Menteri Keuangan, di tengah defisit yang melebar bisa dibaca seperti kinerja yang tampak membaik di permukaan, tetapi belum sehat secara struktur. Mirip pendapatan bertambah, namun ekuitas justru berkurang. Aktivitas ekonomi dan pasar terlihat hidup, tetapi karena defisit dibiayai utang, beban di neraca negara bertambah.
Pertumbuhan atau Ilusi Akuntansi?
Persoalan fiskal Indonesia hari ini bukan sekadar soal defisit atau likuiditas, melainkan soal struktur. PDB boleh tumbuh, IHSG boleh naik, dan likuiditas boleh longgar. Tetapi ketika penerimaan pajak melemah, belanja makin agresif, dan utang menjadi penopang utama, maka pertumbuhan itu lebih menyerupai ilusi akuntansi ketimbang fondasi ekonomi.
Seperti laba yang naik karena utang, bukan karena usaha membaik.
Dalam dunia usaha, kita menyebutnya window dressing: mempercantik laporan tanpa perbaikan substansial. Pertanyaannya: apakah narasi ekonomi nasional hari ini juga sedang mengalami hal serupa?
Saya tidak punya jawaban pasti. Namun ketika ukuran keberhasilan hanya bersandar pada indikator-indikator yang mudah dimanipulasi, sementara struktur fundamental diabaikan, maka skeptisisme bukan sikap pesimis, melainkan kehati-hatian yang masuk akal.
Yang perlu diawasi sekarang adalah bagaimana PDB dihitung dan diukur. Apakah angka pertumbuhan mencerminkan aktivitas ekonomi riil, atau sekadar gelembung dari likuiditas yang mengambang? Sebab pada akhirnya, yang menentukan kesejahteraan rakyat bukan angka di dashboard, melainkan apakah usaha mereka benar-benar bergerak.
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi berdasarkan data yang tersedia secara publik. Bukan nasihat investasi atau keuangan.